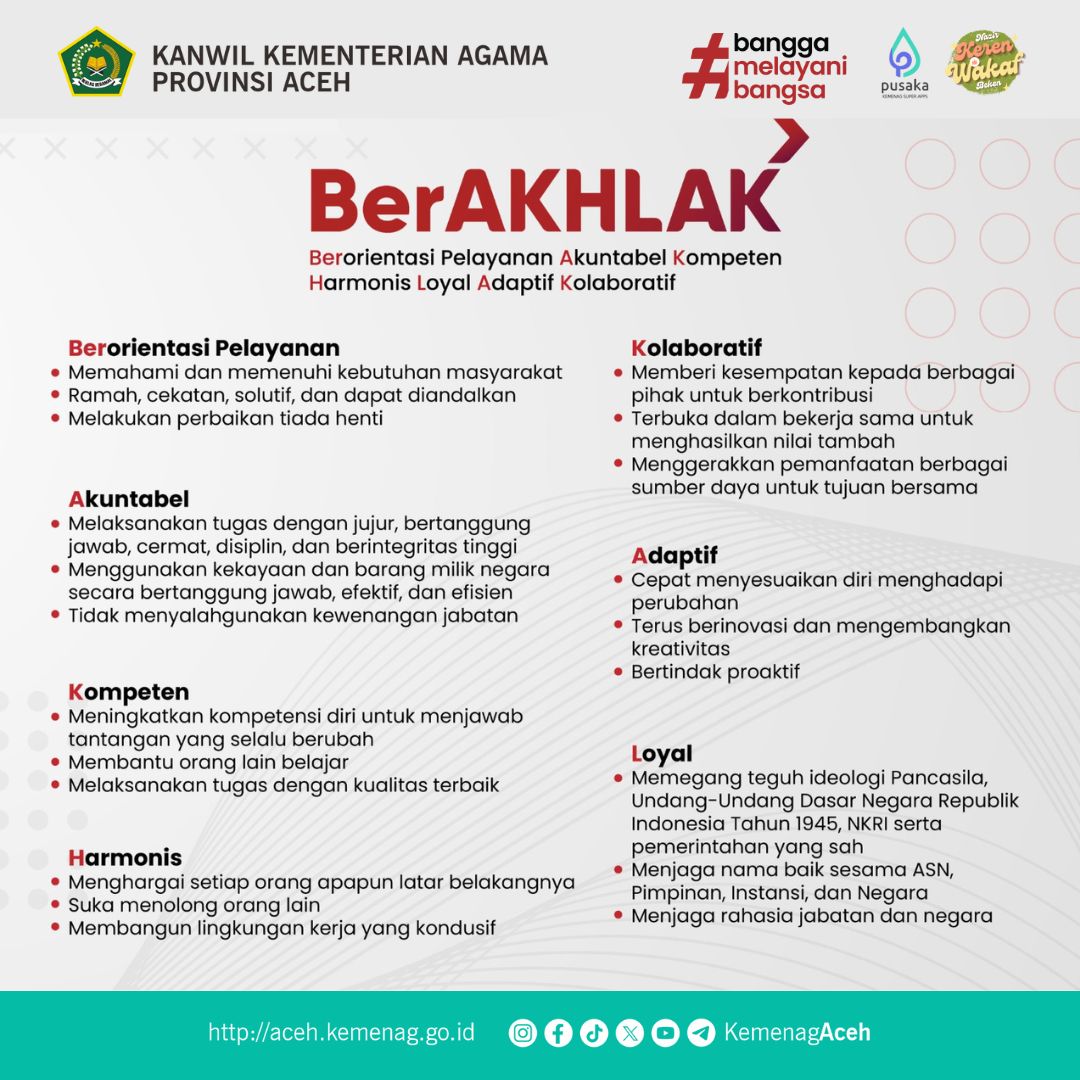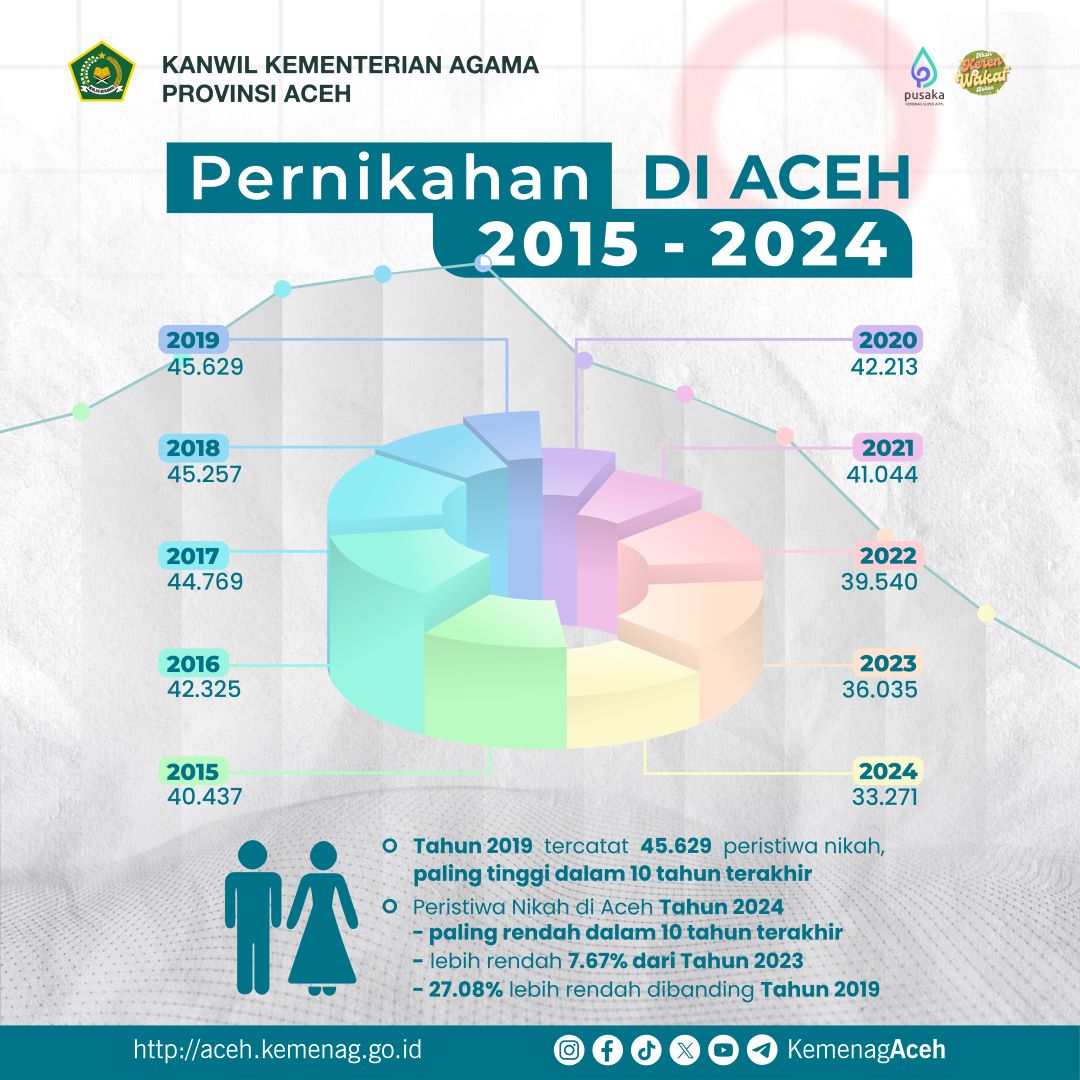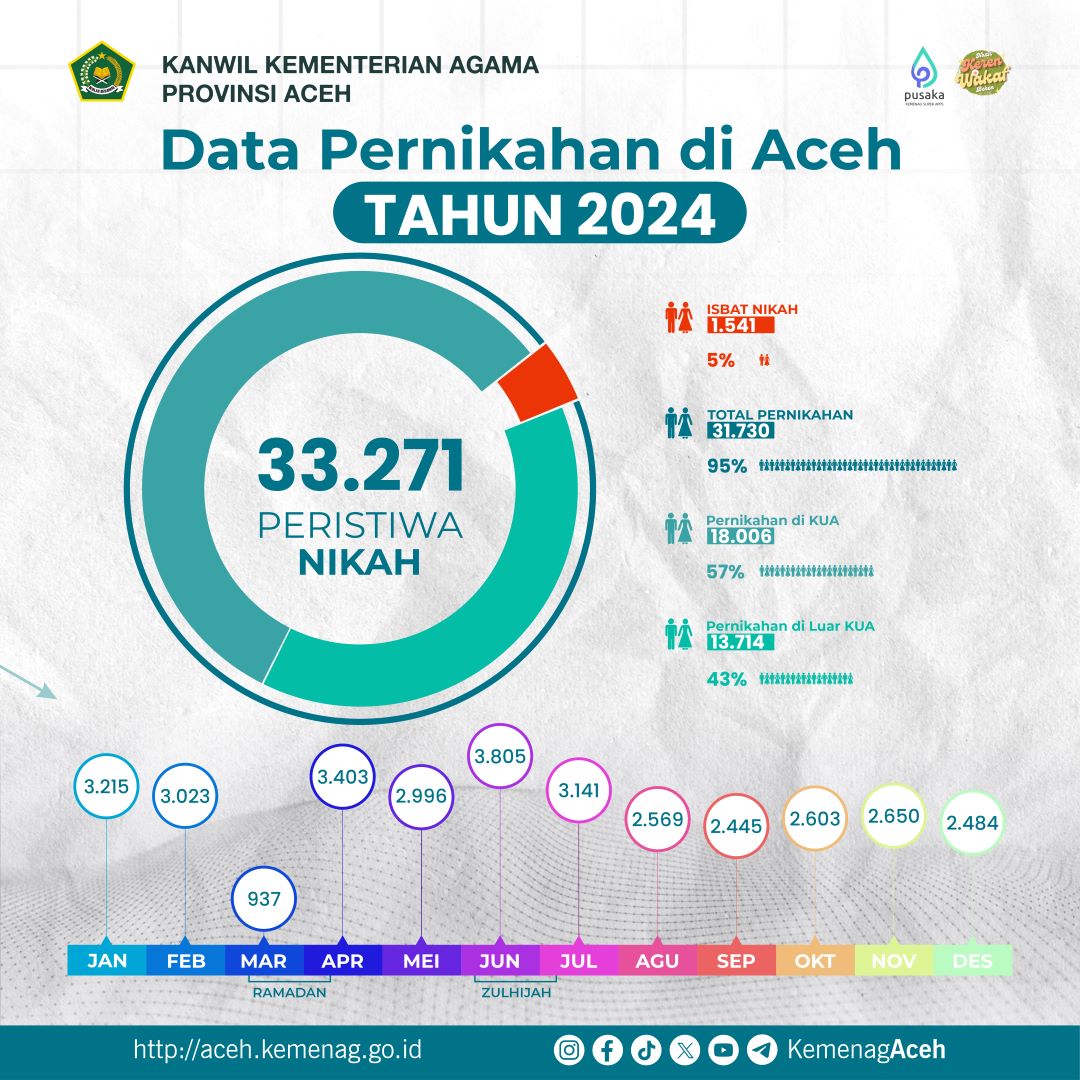- Azhari
- Kakanwil
- Hari Santri
- Halal
- Islam
- Madrasah
- Pesantren
Transformasi Pendidikan dan Pembelajaran di Era Disrupsi
- Penulis
- Dilihat 1255

Transformasi Pendidikan dan Pembelajaran di Era Disrupsi
Oleh Samsul Bahri, S.Pd., M.Pd
Ketua Pokja. MGMP Fisika MA Kota Banda Aceh
Sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih terperangkap dalam model yang berorientasi pada hafalan dan nilai, sebuah realitas yang menimbulkan kegelisahan dan kesalahpahaman.
Artikel ini mengkaji secara mendalam krisis paradigma, khususnya pada aspek penilaian yang menempatkan guru sebagai satu-satunya otoritas evaluasi. Untuk mengatasi masalah ini, artikel ini mengusulkan sebuah model rekonstruksi yang mencakup transformasi penilaian menuju pendekatan holistik, serta membangun akuntabilitas berjenjang dari guru hingga lembaga pendidikan yang melatih mereka.
1. Pendahuluan
Pernahkah kita bertanya, apa yang tersembunyi di balik barisan angka di rapor? Bagi sebagian besar dari kita, rapor adalah vonis. Angka 90 adalah pujian, sementara angka 70 adalah kegagalan. Sejak sekolah dasar, kita dilatih untuk menjadi seorang "pengumpul angka". Di hadapan guru, kita adalah wadah yang harus diisi teori dan rumus.
Di hadapan orang tua, kita adalah proyek yang harus menghasilkan angka sempurna. Tekanan itu menumpuk, mengubah rasa ingin tahu menjadi kecemasan, dan mengubah proses belajar menjadi sebuah perlombaan yang melelahkan.
Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang siswa yang merasa seperti robot. Ia bisa menghafal setiap pasal dalam buku sejarah dan menguasai setiap rumus fisika tanpa salah. Nilai-nilainya selalu sempurna, menjadikannya kebanggaan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hampa.
Pengetahuannya, yang begitu sempurna di atas kertas, terasa asing dan tak relevan dengan kehidupannya. Ia tidak pernah benar-benar bertanya mengapa perang terjadi atau mengapa gravitasi bekerja. Ia hanya tahu bagaimana menjawab soal-soal tentang itu.
Kisah ini bukanlah anomali, melainkan cerminan dari sebuah narasi kolektif. Ada jutaan siswa di luar sana yang, di balik senyum bangga saat menerima rapor, merasa kosong. Mereka tahu cara memenangkan perlombaan pendidikan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memenangkan kehidupan. Mereka lulus dari sekolah dengan ijazah, tetapi tanpa gairah dan pemahaman yang mendalam.
2. Masalah
Sistem pendidikan yang berlaku saat ini, dengan segala niat baiknya, secara tidak sadar telah menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan dilema. Di dalamnya, kita dapat mengidentifikasi beberapa simpul masalah yang saling terkait.
Pertama, budaya obsesi pada nilai. Anak-anak dilatih untuk menghafal, bukan untuk memahami. Ujian dan nilai menjadi tujuan akhir, bukan alat untuk mengukur kemajuan. Hal ini menciptakan sebuah perlombaan di mana kemenangan diukur dari angka, bukan dari kedalaman pemahaman. Siswa, tertekan oleh harapan orang tua dan sekolah, belajar hanya untuk lulus ujian, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Akibatnya, motivasi intrinsik—cinta akan belajar—terkikis.
Kedua, kegagalan mengakomodasi keberagaman. Sistem pendidikan kita dirancang untuk memproses siswa dalam jalur yang seragam. Kurikulum yang padat tidak memberikan ruang bagi perbedaan individu. Akibatnya, siswa dengan bakat di luar jalur akademis, seperti seni atau musik, sering kali merasa terpinggirkan. Fisika, misalnya, seringkali menjadi momok karena diajarkan hanya melalui rumus-rumus abstrak tanpa konteks yang relevan.
Ketiga, jebakan kompetisi sains dan sejenisnya. Pada awalnya, perlombaan seperti OSN, KSM, atau Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), dirancang untuk mengidentifikasi bakat. Namun, dalam praktiknya, kompetisi ini seringkali menjadi simbol tertinggi dari obsesi kita terhadap hasil.
Persiapan yang fokus pada hafalan pola soal dan rumus secara tidak sadar mengikis esensi dari pembelajaran sejati. Pemenang diagungkan, sementara ribuan peserta lainnya merasa gagal. Kompetisi ini mendefinisikan kecerdasan dalam batas yang sangat sempit.
Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa kompetisi dan nilai memiliki peran fungsional. Nilai dapat menjadi standar objektif untuk mengukur penguasaan materi, sementara kompetisi dapat mendorong siswa untuk mencapai potensi maksimal. Namun, masalahnya bukanlah pada alat tersebut, melainkan pada bagaimana mereka dieksekusi. Ketika obsesi terhadap angka mengesampingkan pemahaman dan gairah belajar, alat yang seharusnya baik justru menjadi bumerang.
3. Menuju Penilaian yang Humanis
Perubahan sejati tidak akan terjadi tanpa merekonstruksi sistem penilaian dan akuntabilitas dari akarnya. Inilah inti dari pergeseran paradigma.
Penilaian sebagai Refleksi, Bukan Hukuman. Nilai rapor harus diubah dari vonis menjadi sebuah cermin. Ini adalah refleksi dari sebuah perjalanan, yang menunjukkan di mana posisi siswa saat ini dan di mana mereka bisa pergi. Dalam sistem ini, nilai bersifat sementara dan dapat diubah sesuai dengan usaha dan kemajuan mereka.
Metode penilaian harus terdiversifikasi. Selain evaluasi dari guru, kita harus menerapkan penilaian diri (self-assessment) dan penilaian sebaya (peer-assessment). Proses ini mengajarkan siswa untuk jujur pada diri mereka sendiri dan melatih mereka untuk memberikan umpan balik yang konstruktif.
Fungsi Rapor dan Peran Guru sebagai 'Hakim'. Sistem penilaian yang berlaku saat ini seringkali menempatkan guru sebagai satu-satunya hakim penilai. Nilai rapor—yang diberikan oleh satu orang guru—seringkali dianggap sebagai justifikasi profil siswa yang sesungguhnya: potensi, kepribadian, hingga masa depannya. Doktrinasi ini berdampak besar pada perkembangan psikologi siswa, membuat mereka merasa bahwa identitas mereka hanya diukur oleh angka. Seharusnya, rapor dapat berubah dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa selama bersekolah. Mekanisme penilaian yang fleksibel perlu diatur untuk mengakomodasi pertumbuhan ini.
Memvalidasi Nilai dengan Alat Diagnostik. Memang benar bahwa validitas nilai rapor harus dijaga. Gagasan untuk mengadakan sejenis TKA (Tes Kemampuan Akademik) yang mulai akan dilaksanakan adalah langkah baik. Namun, TKA tersebut, yang hanya dilaksanakan sekali di akhir proses, tidak memberikan kesempatan bagi siswa dan guru untuk melakukan perbaikan.
Agar lebih efektif dan sejalan dengan paradigma baru, dibutuhkan TKA sejenis yang dilaksanakan setiap semester oleh lembaga lokal, seperti Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota, dengan instrumen yang terstandar dan tervalidasi. Tujuan utama TKA semesteran ini bukan untuk memvalidasi rapor, melainkan sebagai alat diagnostik.
Hasilnya harus digunakan oleh guru dan sekolah untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dan kesenjangan kompetensi, sehingga mereka dapat mengambil tindakan perbaikan. Nilai rapor tetap menjadi cerminan holistik dari berbagai aspek, dengan TKA hanya sebagai salah satu dari banyak masukan, bukan satu-satunya penentu.
Akuntabilitas yang Utuh: Dari Siswa hingga Lembaga. Inilah bagian paling penting dari rekonstruksi. Akuntabilitas tidak bisa lagi menjadi beban satu arah yang hanya ditimpakan pada siswa.
Pertama, nilai siswa sebagai umpan balik untuk guru. Di sekolah yang jujur, nilai yang rendah dari siswa bukan lagi kambing hitam, melainkan cermin atas efektivitas pengajaran guru. Jika sebagian besar siswa tidak menguasai sebuah konsep, guru harus menggunakan data ini sebagai umpan balik untuk memperbaiki strategi pengajarannya. Kedua, akuntabilitas lembaga pendidikan guru (LPG).
Secara jujur, LPG kita belum sepenuhnya siap menghadapi era disrupsi digital. Mereka terdiri dari Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), Pusat/Balai Diklat, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Akuntabilitas harus meluas hingga ke institusi ini. Jika lulusan dari sebuah LPG secara konsisten menghasilkan siswa dengan hasil belajar yang kurang memuaskan, maka lembaga tersebut harus bertanggung jawab.
Namun, penting juga untuk mengakui tantangan praktis yang dihadapi guru. Menerapkan sistem penilaian humanis membutuhkan waktu, pelatihan, dan dukungan sumber daya. Oleh karena itu, solusi tidak bisa hanya ditimpakan pada guru. Pergeseran paradigma ini menuntut seluruh ekosistem pendidikan—termasuk LPG dan pemerintah—untuk bertanggung jawab.
4. Membangun Paradigma Pendidikan Baru
Pergeseran paradigma ini menuntut redefinisi peran dari setiap pilar pendidikan. Ini bukan lagi tentang menambal lubang, melainkan membangun pondasi yang sama sekali baru.
Pemetaan Paradigma Pembelajaran
Untuk memahami secara jelas arah perubahan ini, mari kita petakan perbedaan fundamental antara paradigma yang berlaku saat ini dan yang baru.
Paradigma yang Berlaku Saat Ini: Pendidikan sebagai Transaksi Pengetahuan
Paradigma ini memandang pendidikan sebagai proses transfer informasi yang linier dan satu arah. Guru adalah sumber utama pengetahuan, sementara siswa adalah wadah pasif yang bertugas menyerap, menghafal, dan mereproduksi informasi.
Fokus utama adalah pada penyelesaian kurikulum, pencapaian nilai akademis yang tinggi, dan persaingan untuk mendapatkan peringkat terbaik. Hasil akhir dinilai melalui ujian yang mengukur seberapa banyak informasi yang dapat diingat oleh siswa.
Ditambah lagi, tekanan dari orang tua yang dibesarkan dalam sistem lama seringkali mengukur keberhasilan anak dari rapor dan peringkat. Niat baik ini justru tanpa sadar menciptakan tekanan yang mengubah proses belajar anak menjadi perlombaan.
Paradigma Baru: Pendidikan sebagai Perjalanan Pertumbuhan
Paradigma ini memandang pendidikan sebagai sebuah perjalanan holistik di mana siswa adalah aktor utama. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor yang memandu siswa untuk mengeksplorasi, berkreasi, dan memecahkan masalah. Fokusnya bergeser dari "apa yang diajarkan" menjadi "bagaimana siswa belajar dan tumbuh". Tujuan akhirnya adalah mengembangkan kompetensi abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan karakter, yang dinilai melalui proses berkelanjutan dan portofolio.
Peran Negara: Dari Pengendali Menjadi Arsitek Ekosistem. Negara harus mundur dari peran sebagai pengatur tunggal yang mendikte setiap detail kurikulum. Perannya harus bergeser menjadi arsitek ekosistem pendidikan yang menyediakan kerangka kerja yang kuat dan fleksibel. Pemerintah harus menetapkan kompetensi inti yang relevan dengan kebutuhan global, seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi, dan kemudian memberikan otonomi kepada sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal.
Peran Lembaga Pendidikan: Dari Pabrik Menjadi Taman Pertumbuhan. Sekolah dan madrasah harus bertransformasi dari tempat di mana siswa "duduk dan mendengarkan" menjadi lingkungan yang dinamis. Sistem penjurusan yang kaku harus diganti dengan jalur yang lebih cair dan personal. Di mana siswa dapat memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat mereka, bukan berdasarkan tuntutan administrasi.
Peran Guru: Dari Penyampai Materi Menjadi Pemandu Perjalanan
Di era di mana informasi begitu mudah diakses, peran guru sebagai sumber pengetahuan telah usang. Peran baru mereka jauh lebih mulia: menjadi pemandu yang membantu siswa menavigasi lautan informasi, menjadi mentor yang mengajarkan cara berpikir kritis, dan menjadi fasilitator yang merancang pengalaman belajar yang bermakna. Ini adalah pergeseran dari mengajar apa yang harus dipikirkan menjadi mengajarkan cara berpikir.
5. Penutup
Perjalanan menuju reformasi pendidikan adalah maraton, bukan sprint. Namun, dengan visi yang jelas, kita bisa memulai langkah-langkah kecil yang akan memicu perubahan besar.
Mengubah sistem pendidikan kita bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan anak-anak kita tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat di era yang penuh dengan ketidakpastian.
Pada akhirnya, pendidikan yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak informasi yang dapat kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa dalam kita dapat berpikir, seberapa kreatif kita dapat berkreasi, dan seberapa tulus kita dapat berkolaborasi. Ini adalah jalan menuju pendidikan yang berjiwa, sebuah pendidikan yang memandang setiap individu sebagai sebuah alam semesta potensi yang menunggu untuk ditemukan.
Penulis: Samsul Bahri, S.Pd., M.Pd., Ketua Pokja MGMP Fisika MA Kota Banda Aceh
Terpopuler
Informasi
Pemberitahuan Pelaksanaan PAI Fair 2025
Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026
PEMANGGILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS...
Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 H/ 2025 M
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Provinsi Aceh Tahun 1446 H/ 2025 M
Jalan Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242