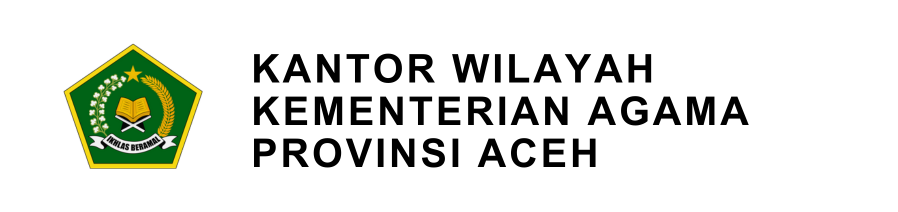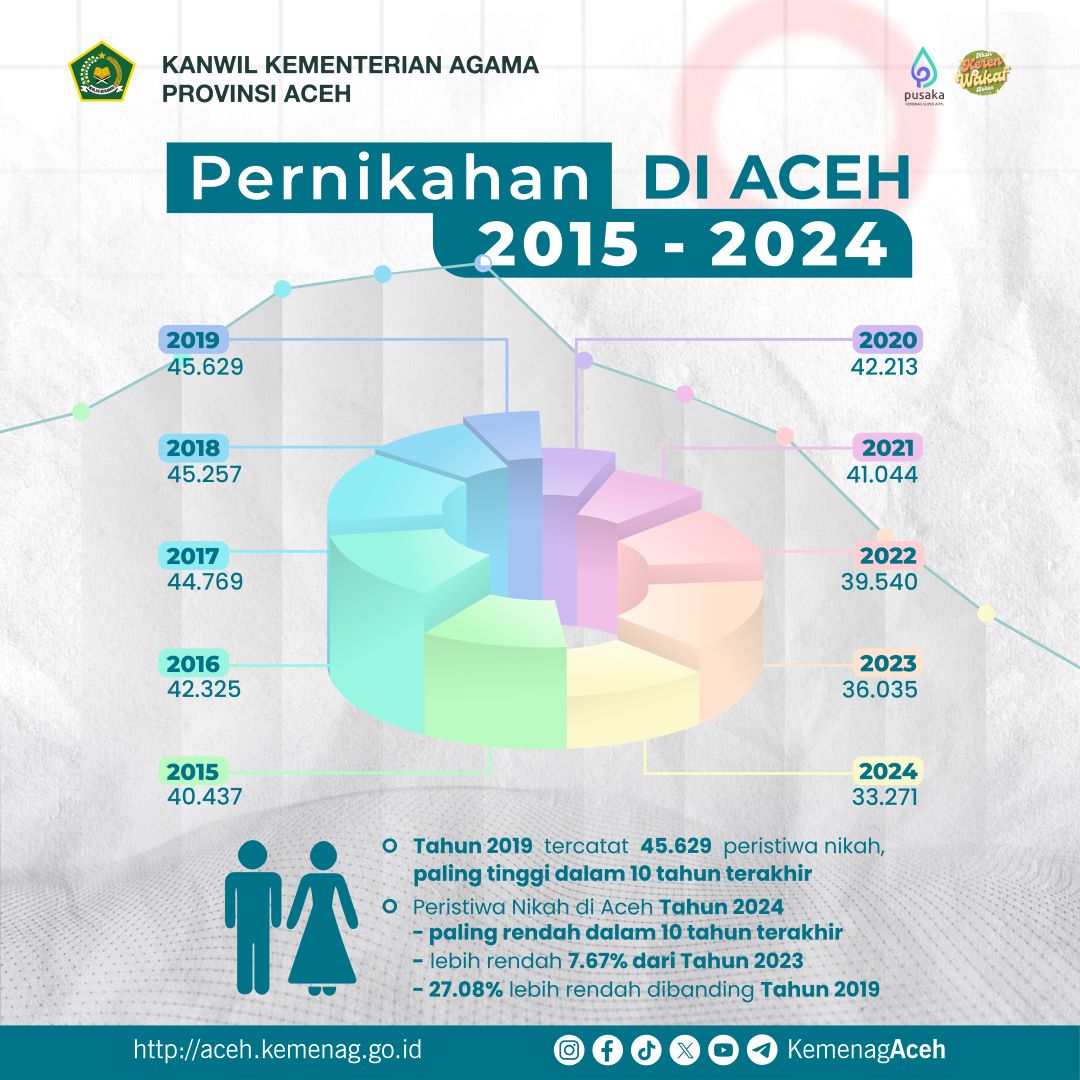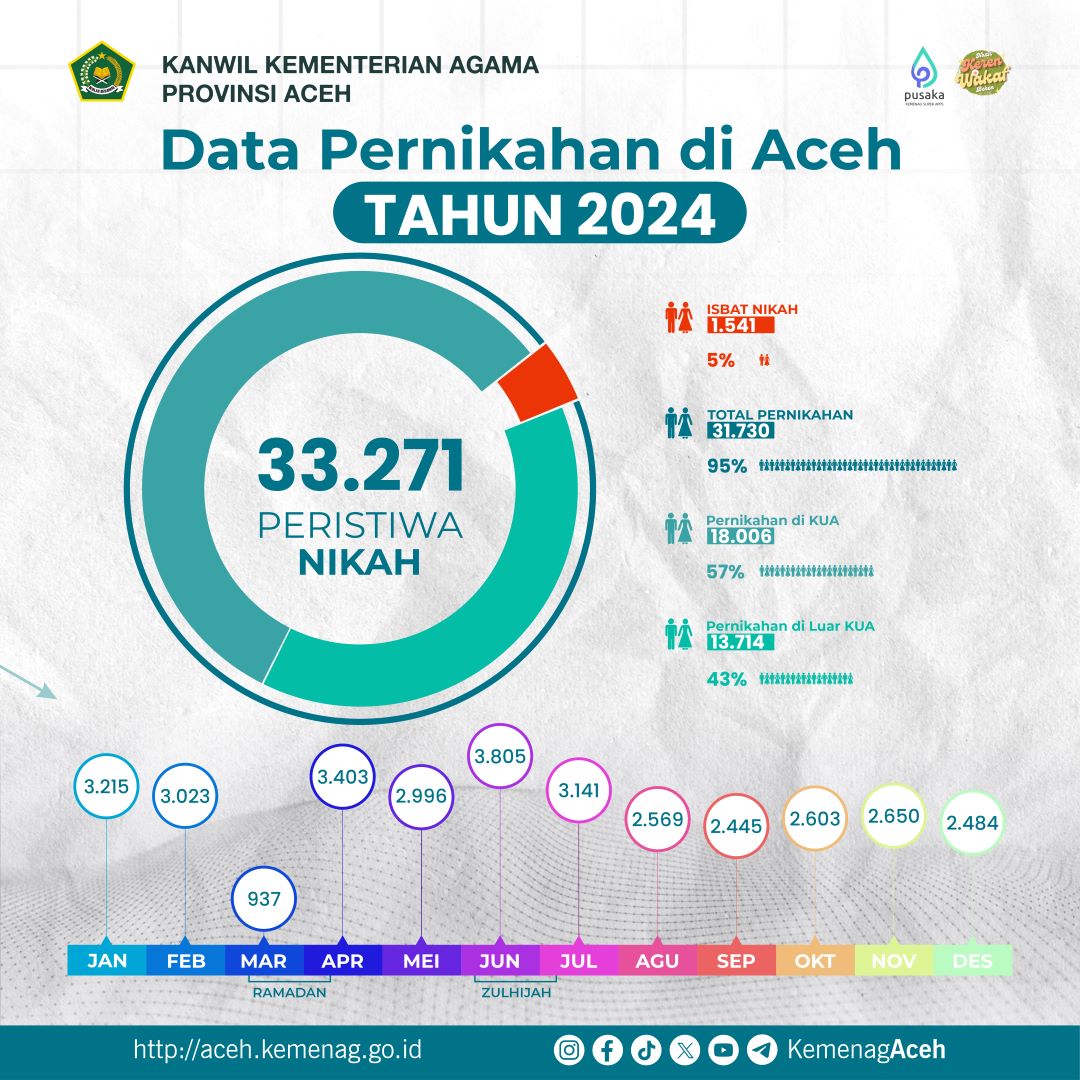- Azhari
- Kakanwil
- Hari Santri
- Halal
- Islam
- Madrasah
- Pesantren
Kisah Relawan PMI Tsunami Aceh
- Penulis
- Dilihat 10557

Cerita ini mulai kutulis sejak Desember 2012 lalu, namun belum ada keberanianku untuk mempublikasinya. Berkat motivasi Bapak Muhammad Sofyan, S.Sos.I (admin web ini, responden majalah Santunan) pada Sosialisasi Jurnalistik untuk Aparatur Kementerian Agama Kab. Aceh Tamiang, akhirnya membuahkan rasa percaya diriku dalam menulis. Terima kasih Pak Yan…
Tanggal 26 Desember adalah tanggal bersejarah sekaligus mengerikan bagiku dan ribuan masyarakat Aceh lainnya. Betapa tidak, gempa dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi Aceh membuat aku dan teman-teman sekontrakan panik bukan main, ditambah lagi teriakkan orang-orang setelah gempa, “Air laut naik!! Lari…lari..”
Tanpa pikir panjang ku ambil ransel kumasukkan berkas kuliah yang kuanggap penting, tak lupa kuselipkan sepotong kain sarung. Lari…
Di sepanjang jalan kulihat orang-orang sudah penuh sesak, mesjid menjadi tujuan mereka. Kesitu pula aku dan teman-teman menuju. Tak merasa aman di mesjid teman-temanku kembali lari ke tempat yang lebih jauh. Kuputuskan di mesjid inilah tempat paling aman untukku meskipun harus terpisah dengan teman-temanku. Di lantai dua masjid itu kulihat ratusan orang terbaring lemah dengan luka-luka bekas hantaman tsunami. Iba hatiku melihatnya, terpikir olehku, “Dalam keadaan sehat seperti ini, apa yang bisa kulakukan untuk mereka? Hanya sepotong kain sarung satu-satunya yang sempat kubawa baru kusedekahkan untuk seorang pengungsi.”
Aku pun tidak ingat siapa orang itu, mungkin ada di antara yang membaca ini pernah menerima kain sarung dariku? Lalu kuberanikan diri untuk turun dari masjid (karena pada saat itu sering terjadi gempa susulan, semua takut akan ada tsunami susulan), kucari botol minuman bekas lalu kuisi dengan air kran tempat wudhu’ masjid. Kubawa dan kutawarkan kepada mereka yang terluka. Puluhan kali naik turun mesjid membuat kakiku pegal.
Saat beristirahat sejenak kulihat salah seorang teman sekampusku dipapah ibunya naik ke masjid (Yuyun Kirana namanya, sekarang bertugas sebagai staf di Dinas Syari’at Islam Kabupaten Nagan Raya). Ternyata dia terseret arus tsunami dan sepotong kayu tertancap di pahanya. Kutemani dia dan kulakukan apa yang bisa untuk membantu dia. Tak lama kemudian datang pula teman yang lain dengan luka-luka yang sangat parah, kali ini laki-laki M. Nur Ahmadi namanya. Sudah ada dua orang yang harus menjadi prioritas perhatianku, pikirku.
Malam pun tiba, aku pamit kepada kedua temanku untuk bergabung dengan kelompok mahasiswa se-daerah asalku karena kudengar kami akan dijemput oleh mobil kiriman dari pemerintah daerah kami. Tak terasa karena kelelahan aku tertidur di samping mereka. Saat terbangun kulihat tak ada lagi mereka di sampingku. Aku sendirian. Kutanyakan kepada orang-orang yang mungkin melihat. “Mereka sudah pulang dijemput mobil L300,” itulah jawaban yang kudapat.
Sedih hatiku tak ada seorangpun yang membengunkan aku. Mungkin mereka tak sempat memikirkan orang lain di saat-saat begini. Aku ikhlas ditinggal mereka. Kuputuskan kembali ke masjid untuk bersama dengan teman-temanku yang sedang sakit.
Esok harinya mereka dijemput oleh keluarga masing-masing. Kemana aku harus pergi sekarang? Mau pulang kampung aku tidak tahu harus pulang dengan apa, uang seribupun tak ada. Teman yang kukenal sudah tak ada, memang Yuyun mengajakku pulang bersamanya ke Nangan Raya. Tapi aku terpikir keluargaku pasti menunggu kabar dariku, masih hidupkah aku atau sudah tiada. Saat bingung itulah kulihat seorang abang leting yang tinggal dekat kontrakanku sedang duduk di bawah tenda Palang Merah Indonesia (PMI).
Aku mendekat dan kuceritakan keadaanku. “Ya udah, untuk sementara kamu di sini aja, mungkin nanti ada mobil yang pulang minta numpang aja,” saran dia. (Hardiman namanya, semoga bang Har sekeluarga sehat).
Sesaat kemudian datang sebuah mobil Ambulance, turun beberapa orang yang belakangan baru aku tahu mereka disebut “relawan”. Salah seorang dari mereka menawarkan aku makan. “Udah makan dek? Makan lah apa yang ada, jangan malu-malu anggap aja rumah orang,” selorohnya.
Saat itu aku menilai tidak etis memang dalam keadaan genting seperti ini masih saja bercanda. Tapi kemudian setelah lama aku bergabung di PMI baru aku mengerti bahwa seloroh dan candaan memang perlu untuk membangkitkan semangat dalam bertugas sebagai pekerja kemanusiaan.
Dua hari berlalu. Mayat-mayat korban tsunami semakin banyak berjejer di pekarangan mesjid membuat semakin sempitnya areal untuk pengungsi. Di tengah malam datang lah beberapa pengungsi ke tenda kami yang sedang beristirahat setelah seharian ada yang mengevakuasi mayat dan ada yang bertugas mengobati luka-luka para pengungsi. Mereka marah-marah dan menyuruh kami memindahkan mayat-mayat malam itu juga. Rupanya beberapa pengungsi protes kepada PMI yang meletakkan mayat di pekarangan mesjid karena bau mayat yang sudah mengganggu para pengungsi. Malam itu juga para relawan bekerja menggali kuburan massal dan memindahkan mayat-mayat tersebut ke tempat yang agak jauh dari pengungsian sampai pagi menjelang. Begitulah nasib sebagian pekerja kemanusiaan mungkin.
Mayat-mayat korban tsunami dianggap menjadi tanggung jawab mereka, padahal itu menjadi tanggung jawab kita semua. Pengalaman seperti itu tidak hanya terjadi sekali tetapi berulang kali masyarakat protes kepada relawan, bukan hanya dalam hal evakuasi mayat tapi dalam pendataan korban apalagi dalam pendistribusian bantuan. Sangat wajar rasanya karena mereka sedang membutuhkan perhatian dari orang lain disaat mereka baru saja kehilangan keluarga, sanak saudara, harta dan sebagainya.
Hampir seminggu musibah berlalu tapi aku belum menghubungi keluargaku, maklum saja saat itu belum ada alat komunikasi apapun di kampungku. Mereka belum tau keadaanku sama sekali. Sedangkan ayahku yang berhari-hari pergi mencariku ke Banda Aceh pulang dengan tangan kosong. Tiba-tiba pada pagi sabtu itu ada berita baik dari relawan yang pernah berseloroh denganku saat pertama kali aku bergabung dengan PMI. Sekarang aku kenal dia, nama aslinya Radhi, tapi teman-teman relawan memanggilnya Abu, Abu Radhi.
“Ada mobil bawa bantuan dari Unsam Langsa, katanya mau pulang hari ini. Mau ikut pulang?” Alhamdulillah…
Sampai di rumah jam 02.00 WIB dini hari Minggu, ibuku menangis menyambut kepulanganku. Kupeluk ibuku. Bagaimana aku bisa meminta untuk kembali membantu pengungsi di Banda Aceh dengan keadaan ibuku seperti ini..batin hatiku. Paginya setelah aku di Peusijuk (tepung tawar) se ala kadarnya, kusampaikan niatku untuk kembali ke Banda Aceh. Betapa terkejutnya keluargaku, terutama ibuku. Tetapi akhirnya mereka mengikhlaskan kepergianku.
Hari Minggu itu juga aku kembali ke Banda Aceh dengan tujuan membantu para pengungsi juga membantu para relawan yang telah menampungku selama seminggu, setidaknya membantu memasak di dapur umum untuk mereka.
Sejak hari itu aku resmi menjadi bagian dari organisasi kemanusiaan tersebut sebagai Tenaga Suka Rela (TSR) pada Posko PMI Aceh di depan Kampus Unsyiah Banda Aceh dan saat itu aku mulai dekat dengan Abu Radhi. Seminggu setelah aku kembali ke Banda Aceh, beliau ditarik untuk bergabung ke Posko Utama penanggulangan bencana PMI Aceh yang waktu itu berada di Lueng Bata. Sejak saat itu komunikasi antara kami terputus.
Sampai suatu hari beliau datang ke posko tempatku bertugas dengan membawa sebuah handphone untuk diberikan kepadaku. Rupanya selama ini beliau ditugaskan dalam evakuasi mayat di daerah Leupung Aceh Besar. Setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai, semua relawan pada posko-posko pembantu dibubarkan dan kembali pada kegiatan masing-masing karena pengungsi sudah tidak ada lagi. Pengungsi pulang ke rumah masing-masing bagi yang masih punya rumah dan ditempatkan ke barak-barak bagi yang tidak memiliki rumah.
Aku kembali kuliah dengan begitu banyak pengalaman sebagai relawan, merawat luka-luka pengungsi, memegang dan mengangkat mayat-mayat. Padahal sebelumnya aku sangat takut dengan mayat. Melakukan assessment para pengungsi sampai melakukan pendistribusian bantuan ke pelosok-pelosok Aceh Besar. Mulai saat itu aku kembali sibuk dengan kuliahku, sampai suatu hari Bang Raji (panggilanku buat Abu Radhi) mengabarkan bahwa Palang Merah Amerika bekerja sama dengan PMI Aceh menjalankan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan membutuhkan dua orang relawan.
“Satu orang sudah ada, yang satu lagi ditawarkan ke Abang. Cuma Abang kurang tertarik dengan perkantoran. Kalo mau biar Abang daftarkan,” tawarnya.
Besoknya aku dipanggil untuk bekerja sebagai relawan membantu administrasi di kantor. Alhamdulillah tidak rugi aku kursus komputer dulu waktu masih sekolah SMU di kampung. Di sini ilmu itu terpakai dan aku diizinkan kuliah sambil bekerja. Sekarang aku siap menjadi relawan kembali, bedanya kali ini aku dapat honor.
Dengan honor yang lumayan menurutku sebagai mahawiswa yang tidak memiliki tanggungan apa-apa, terpikir olehku bagaimana aku mempergunakan honorku dengan bijak. Teringat akan janjiku kepada kakak dan adik-adikku waktu aku mau berangkat kuliah dulu, bahwa aku akan mencari kerja sambilan kuliah agar bisa membuat rumah yang layak untuk kita nanti.
Kusampaikan keinginanku kepada Bang Raji yang baru pulang bertugas dari Lhoong Aceh Besar. Memang beliau sering bertugas di luar Banda Aceh. Tanpa kuduga betapa mulia hatinya. “Kita jual kereta Abang aja dulu untuk beli bahan bangunan, nanti upah tukangnya kita cicil dengan honor adek,” begitulah beliau menanggapinya.
Sedikit demi sedikit akhirnya pada awal tahun 2009 rumah yang kami rencanakan dan diidamkan oleh adik-adikku selesai juga. Setidaknya biarpun cuma rumah dengan ukuran 7×9M ditambah sedikit dapur, keluargaku tidak lagi menampung air ketika hujan dan Alhamdulillah kereta yang dulu dijual telah kuganti dengan kereta New Supra X 125 tahun 2008.
Sepanjang perjalanan kisah kami, memang rencana hidup berumah tangga yang lebih kami utamakan. Maka ketika beliau kembali bertugas dari Calang dan Meulaboh beliau berkata, “Abang ada sedikit tabungan untuk kita beli emas, adek mau kan kalo kita tunangan dulu?”
Kusampaikan niat kami kepada orang tuaku dan diterima dengan senang hati. Akhirnya pada tanggal 23 Februari 2008 kami bertunangan. Karena aku masih kuliah di semester tujuh, keluargaku memberi tangguhan pernikahannya dilaksanakan setelah aku selesai kuliah. Setelah bertunangan aku semakin giat menyelesaikan skripsiku yang memang judulnya telah diterima dalam seminar proposal judul skripsi saat aku masih semester enam.
Sambil bekerja untuk mengirimkan uang bangun rumah aku berusaha menyelesaikan skripsiku hingga pada akhir semester tujuh skripsiku disetujui (di ACC) oleh pembimbing I dan pembimbing II, sementara ujian konfrehensif juga sudah selesai kuikuti, harapanku bisa mengikuti sidang munaqasyah pada akhir semester tujuh.
Namun betapa sedihnya aku saat itu, aku tidak bisa mendaftar sidang karena ada satu mata kuliah yang kuambil di semester tujuh belum dikeluarkan nilainya. Memang nilainya baru keluar pada akhir semester, sementara pendaftaran sidang telah ditutup. Jadilah aku menunggu satu semester lagi hanya untuk menunggu nilai satu mata kuliah untuk bisa mendaftar sidang. Akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2008 aku resmi diwisuda dan menyandang gelar Sarjana Hukum Islam. Dengan izin Allah pula dua bulan kemudian tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2008 aku resmi menjadi isteri dari Radhi,S.Pd.I yang telah banyak berjasa dalam hidupku.
Pada tahun 2009 aku lulus sebagai salah seorang penerima beasiswa spesialisasi mengajar dari Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry dalam program Akta IV. Dengan padatnya jadwal kuliah dan kesibukan pekerjaan masing-masing, kami terpaksa menunda resepsi pernikahan kami. Baru pada tanggal 30 Mei 2009 kami mengadakan resepsi pernikanan di rumah yang sama-sama kami bangun dulu. Betapa harunya aku bersanding dengan orang yang sangat kucuntai dalam istana yang kami bangun dengan cinta dan pengorbanan. Dengan izin Allah pula pada tanggal 10 April 2010 kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan, mirip ayahnya. Semoga berakhlak mulia seperti ayahnya. Lahir melalui operasi seacar di Rumah Sakit Cut Nyak Dien Langsa anak kami diberikan nama Zdaki Aulia oleh suamiku.
Menurutnya nama itu terinspirasi dari salah seorang pembimbing skripsiku Bapak Dr.Zaki Fuadh Chalil,MA karena intelektualitas dan kebaikan hatinya dalam membimbingku menyelesaikan skripsiku. Semoga anak kami menjadi manusia intelek dan berbudi pekerti luhur seperti beliau. Dan pada akhir 2012 lalu tepatnya 19-12-2012 kami kembali dikaruniai seorang putra lagi yang kami beri nama Richad Saydi, berdasarkan penalaran bahasa Arab ku yang pas-pasan, terinspirasi dari Saidina Muhammad mungkin mengandung makna panglima yang memberi petunjuk, semoga….
Dan di akhir ceritaku izinkan aku memanjatkan sepenggal doa, doa yang mungkin sering dilantunkan oleh insan-insan yang saling mencinta dalam ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
“Ya Allah… Perkenankanlah aku bersamanya sampai ajal memisahkan kami, dan izinkanlah aku mati sedetik sebelum kematiannya, agar kami tak pernah merasa terpisahkan satu sama lain.” Aamiiin…. [Siti Aisyah/y]
Terpopuler
Informasi
Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026
PEMANGGILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS...
Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 H/ 2025 M
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Provinsi Aceh Tahun 1446 H/ 2025 M
Imsakiyah Ramadan 1446 H/ 2025 M
Jalan Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242